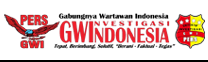Jakarta |gabungnyawartawanindonesia.co.id.- Pada hari rabu 08 oktober 2025, Pada perkara tindak pidana asusila, di mana bukti fisik sering terbatas, keterangan saksi terutama korban, sering menjadi pintu utama untuk membuktikan terjadinya tindak pidana.
Dalam perkara tindak pidana asusila, keberadaan saksi memegang peran yang sangat menentukan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tindak pidana asusila yang umumnya terjadi di ruang privat, minim saksi mata, serta seringkali tidak meninggalkan bukti fisik yang kuat.
Maka, keterangan saksi terutama korban yang mengalami langsung, menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembuktian di pengadilan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi tentang saksi secara tegas dalam Pasal 1 angka 26, yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”
Selain itu, KUHAP juga menegaskan kedudukan keterangan saksi dalam pembuktian.
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : 1.Keterangan Saksi ; 2.Keterangan Ahli ; 3.Surat : 4.Petunjuk ; 5.Keterangan Terdakwa ; Dari ketentuan dimaksud, tampak jelas sistem hukum acara pidana Indonesia menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu pilar penting dalam menemukan kebenaran materiil.
Pada perkara tindak pidana asusila, di mana bukti fisik sering terbatas, keterangan saksi terutama korban, sering menjadi pintu utama untuk membuktikan terjadinya tindak pidana.
Dalam praktiknya, saksi kasus asusila dapat beragam bentuk. Ada saksi fakta, yakni orang yang benar-benar melihat atau mengalami peristiwa dan ada saksi korban, yaitu pihak yang langsung menjadi objek perbuatan asusila.
Tidak jarang pula muncul keterangan saksi de auditu, yakni keterangan yang didasarkan pada apa yang didengar dari orang lain.
Keterangan de auditu sempat menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak memenuhi unsur “melihat, mendengar, atau mengalami sendiri”. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan terobosan penting.
Mahkamah Konstitusi menegaskan keterangan saksi tidak harus dimaknai secara sempit, sepanjang keterangan tersebut relevan dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.
Dengan putusan ini, ruang pembuktian menjadi lebih fleksibel, khususnya dalam perkara tindak pidana asusila, di mana keterangan langsung sering sulit diperoleh.
Meski demikian, bobot keterangan saksi tetap harus dinilai secara hati-hati oleh hakim. KUHAP menegaskan bahwa keyakinan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada satu alat bukti semata, melainkan harus didukung alat bukti lain yang sah.
Artinya, meskipun keterangan korban sebagai saksi sangat penting, tetap diperlukan dukungan dari bukti tambahan, baik berupa visum et repertum, keterangan ahli, maupun petunjuk lainnya.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam kasus asusila, saksi sering menghadapi tekanan, ancaman, bahkan stigma sosial yang berat.
Untuk itu hadir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014.
Regulasi ini memberikan hak kepada saksi dan korban, untuk mendapatkan perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, bahkan kompensasi dan rehabilitasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi garda terdepan dalam memastikan perlindungan tersebut berjalan secara nyata.
Dalam tataran teknis peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan khusus. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi tonggak penting.
Dalam Pasal 5 Perma tersebut, ditegaskan Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum wajib : tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan ; tidak mengizinkan pertanyaan yang menyinggung pengalaman seksual masa lalu korban atau saksi yang tidak berkaitan dengan perkara ; menghindari penggunaan bahasa atau pandangan yang bias gender.
Ketentuan ini jelas merupakan larangan bagi hakim untuk melakukan victim blaming dalam persidangan, yang selama ini kerap dialami korban asusila.
Untuk memperkuat implementasi, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menegaskan agar Perma tersebut dipedomani dalam setiap persidangan.
Demikian pula SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Korban dalam Perkara Tindak Pidana, yang menekankan kewajiban hakim menjaga martabat korban. Di dalamnya ditegaskan Hakim dilarang memperlihatkan barang bukti atau alat bukti yang tidak relevan dengan perkara namun berpotensi merendahkan martabat korban, serta wajib menjaga agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma tambahan.
Dengan adanya kerangka hukum yang mencakup KUHAP, KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, kedudukan saksi dalam perkara tindak pidana asusila semakin jelas, ia bukan sekadar alat bukti, melainkan subjek penting yang harus dijaga martabat dan keamanannya.
Tantangan besarnya, adalah bagaimana implementasi di lapangan benar-benar mengutamakan keadilan substantif, sehingga korban mendapat ruang aman untuk bersuara, sementara hak-hak terdakwa tetap terjamin dalam kerangka fair trial.
(Red/Sumber Penulis : Derry Yusuf Hendriana/Humas MA)